Perpu, Veto Atas Legistorkrasi
Ditulis oleh: Dr. Charles Simabura, SH., MH
Diterbitkan oleh https://www.hukumonline.com, 27 Oktober 2020
Kontroversi RUU Cipta Kerja terus berlanjut terutama pasca paripurna DPR tanggal 5 Oktober lalu. Dugaan pelanggaran konstitusi terutama mengarah pada validitas antara RUU yang disetujui bersama dengan yang akan diundangkan oleh Pemerintah. Setidaknya telah beredar enam versi RUU Cipta Kerja di tengah tuduhan penyebaran hoaks oleh pemerintah. Padahal, Pemerintah dan DPR sendiri tidak mampu menyajikan informasi yang valid mengenai RUU Cipta Kerja.
Praktik demikian seakan benar dan dapat dibenarkan. Pemerintah dan DPR terus berlalu, bergeming sedikitpun atas tekanan publik. Desakan agar segala persoalan formil dan materil UU Cipta Kerja diselesaikan melalui Perppu ditentang sedemikian rupa. Perppu dianggap mustahil diterbitkan, para pengkritik dikanal agar menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
Gegap gempita Pemerintah dan DPR yang hendak memindahkan pertanggungjawaban publik mereka kepada MK patut dicurigai pasca perubahan UU MK beberapa waktu lalu. Legislasi “ugal-ugalan” malah diselesaikan dengan logika normal konstitusional, sungguh suatu yang bertolak belakang. Demokrasi telah menjelma menjadi legistokrasi berpadu dengan oligarki despotik.
Jika dipadankan dengan isltilah populer lain semisal: aristokrasi, demokrasi dan juristokrasi, legistokrasi dimaknai dengan kekuasaan oleh, dari dan untuk legislator. Legislator diartikan sebagai para pembentuk hukum/undang-undang (Black’s Law Dictionary, 2009). Dalam sistem parlementer, parlemen dan pemerintah diposisikan sebagai legislator. Sedangkan dalam sistem presidensil, DPR adalah legislator minus pemerintah.
Berdasarkan konstitusi, Indonesia menganut model join legislasi (Saldi Isra, 2010) di mana Presiden dan DPR bertindak selaku legislator dalam proses legislasi. Meskipun konstitusi menyatakan kekuasaan legislasi berada pada DPR, namun sebuah UU haruslah dibahas dan disetujui bersama Presiden (Pasal 20 Ayat (1) dan (2)). Artinya, tidak ada pembelahan kekuasaan di bidang legislasi antara Presiden dan DPR termasuk dalam mengajukan RUU.
Konsep kesetaraan kuasa legisalasi DPR dan Presiden yang dianut Indonesia jelas berbeda dengan model legislasi presidensial pada umumnya. Negara seperti Amerika Serikat, Brazil dan Filiphina menempatkan kekuasaan legislatif di tangan Kongres (All legislative power vested by the Congress). Terdapat pemisahan kekuasaan dalam bidang legislasi antara Presiden dan DPR.
Presiden tidak terlibat dalam pembahasan dan persetujuan RUU (bill) di Kongres. Presiden hanya diberi hak veto (penolakan) atas UU yang disetujui Kongres. Atas veto tersebut, Kongres dapat membatalkannya melalui pemungutan suara. Jika mayoritas menolak maka UU berlaku. Sebaliknya jika menerima maka UU tidak berlaku atau direvisi sesuai kebutuhan.
Model veto pada sistem presidensial tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia. Penolakan Presiden atau DPR hanya dapat disampaikan dalam sidang paripurna persetujuan bersama. Terhadap RUU yang telah disetujui wajib diundangkan. Jika Presiden menolak mengundangkan, menurut konstitusi UU berlaku setelah 30 hari sejak persetujuan bersama.
Terhadap UU yang telah disetujui bersama namun ternyata mendapat penolakan publik maka setidaknya terdapat dua pilihan konstitusional yaitu executive review melalui Perppu atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Penerbitan Perppu dapat saja menjadi preseden baru dan bahkan konvensi ketatanegaraan di bidang legislasi. Perppu menjadi semacam “veto” oleh Presiden terhadap UU yang telah disetujui bersama.
Praktik penolakan Presiden atas UU yang telah disetujui bukanlah hal baru. Presiden Megawati tercatat pernah menolak menandatangani empat UU (Hukumonline.com, 22/2/2018). Megawati tidak mengeluarkan Perppu karena belum ada gagasan untuk itu. Presiden SBY-lah yang pertama kali mempraktikan penerbitan Perppu pasca persetujuan bersama UU demi mendengarkan aspirasi publik. Perppu 1/2014 dikeluarkan guna mengembalikan pemilihan kepala daerah secara langsung yang sebelumnya dipilih oleh DPRD.
Jokowi setidaknya telah dua kali tidak menandatangani UU yaitu perubahan UU MD3 (2018) dan UU KPK (2019). Khusus UU KPK, Jokowi nyaris menerbitkan Perppu tetapi batal. Akhirnya pilihan jatuh pada pengujian UU KPK di Mahkamah Konstitusi.
Perppu sebagai Veto atas UU Cipta Kerja
Setidaknya terdapat dua alasan konstitusional Presiden dapat “memveto” UU melalui Perppu. Pertama, secara faktual UU dibahas oleh menteri terkait dan bukan tidak mungkin Presiden tidak mengetahui detail isi RUU. Meskipun para menteri melaporkan perkembangan pembahasan namun tidak semuanya tersampaikan. Kedua, Presiden selaku kepala negara dapat saja mengambil posisi berbeda dari para pembahas dikarenakan perkembangan situasi ketatanegaraan.
Jika dalam sistem parlementer seorang raja dapat membatalkan keberlakuan UU demi tegaknya konstitusi maka sistem presidensial mensematkan kuasa tersebut pada Presiden. Semangat inilah yang melatarbelakangi rumusan Pasal 22 UUD NRI 1945 di mana dalam hal ikhwal kegentingan memaksa Presiden dapat menerbitkan Perppu.
Kegentingan memaksa menurut Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU (putusan MK 138/PUU-VII/2009). Dalam hal ini, Presiden memiliki hak prerogratif untuk menyatakan bahwa desakan dan penolakan publik sebagai sebuah kegentingan memaksa.
Dengan demikian atas dasar kemendesakan maka penerbitan Perppu menjadi ultimum premium dalam membatalkan UU Cipta Kerja. Perppu merupakan langkah konstitusional untuk meredakan kekecewaan publik. Publik yang menolak harus dibujuk agar kembali kepada konstitusi. Penerbitan Perppu merupakan persuasi Presiden terhadap publik yang terlanjur tak percaya.
Penerbitan Perppu tidaklah pengangkangan atau pengkhiatan terhadap DPR. Secara konstitusonal “Perppu veto” akan diajukan kembali kepada DPR. Mekanisme ini mirip dengan persetujuan Kongres atas veto Presiden pada sistem presidensial sehingga dibutuhkan kembali “persuasi” Presiden agar DPR menerima Perppu tersebut. Materi muatan Perppu dapat saja membatalkan seluruh atau sebagian saja dari isi UU Cipta Kerja. Jika langkah ini ditempuh maka akan membuka ruang pembahasan kembali beberapa subtansi krusial.
Dengan demikian presiden hadir sebagai kepala negara yang mempersuasi seluruh warga bangsa dan tidak hanya para legislator maupun investor. William G. Howell menyatakan bukankah hakikat dari kekuasaan Presiden adalah kemampuan untuk “membujuk” (Presidential Power is the Power to Persuade, 2003). Sudah saatnya presiden mengoptimalkan kuasa konstitusionalnya guna mewujudkan kesejahteran sosial (the pursuit of happiness, 2006).
Seandainya hal demikian tidak ditempuh, legistokrasi menjadi nyata dalam proses legislasi Indonesia. Menurut Mahfud MD (2006), UU demikian dapat dikategorikan sebagai UU dengan karakter ortodok karena represif, minus partisipasi dan top down. Pepatah mengatakan: jika sesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan.
Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/a/perppu-veto-atas-legistokrasi-lt5f9794c08ea76/?page=1


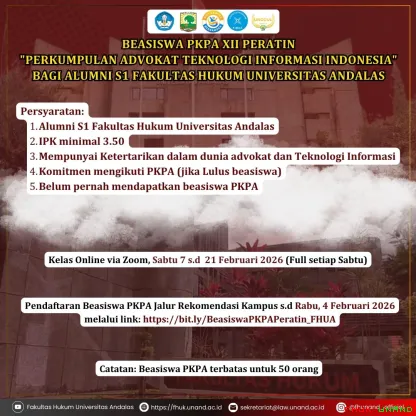

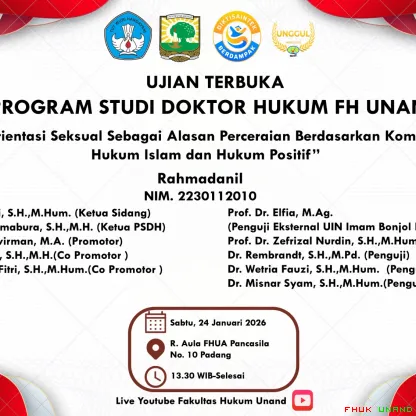
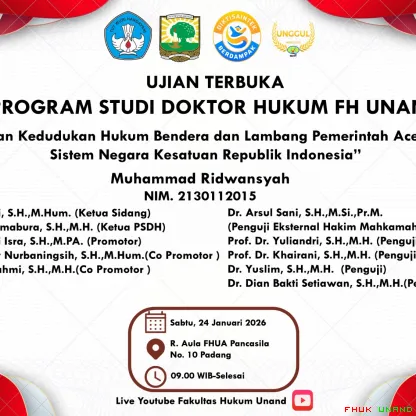
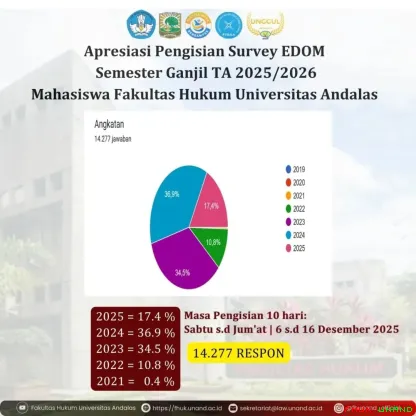

Komentar