Menyoal Majlis Kehormatan
Ditulis Oleh Ilhamdi Putra, SH., MH
Diterbitkan timesindonesia.co.id, 05 Januari 2024
MK mengumumkan komposisi Majelis Kehormatan MK (MKMK) pada Rabu (20-12-2023) lalu. Berbeda dari yang sudah-sudah, kini MKMK bersifat permanen dengan masa kerja setahun dan tidak lagi kasuistik. Sekalipun terbilang cukup progresif dengan meninggalkan desain ad hoc, MKMK masih memiliki beberapa catatan dan kecacatan yang belum terobati.
Merujuk ketentuan Pasal 27A ayat (2) UU MK, pembentuk undang-undang menentukan komposisi MKMK yang salah satunya adalah Hakim Konstitusi aktif. Pada ayat (7) di pasal itu pembentuk undang-undang memberi keleluasaan kepada MK untuk menyusun organisasinya, termasuk menentukan anggota MKMK. Atas dasar itulah kemudian MK memasang mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, yang merepresentasikan tokoh masyarakat, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Yuliandri dari unsur akademisi hukum, dan Hakim Konstitusi aktif, Ridwan Mansyur.
Dari sini persoalan mulai terlihat. Bagaimana mungkin MKMK yang bertugas mengadili Hakim Konstitusi atas kasus pelanggaran etik dapat bersih dari isu imparsialitas bila anggotanya dipilih oleh Hakim Konstitusi dan dilantik oleh Ketua MK? Kekonyolan inilah yang terjadi pada MKMK yang diisi Jimly Asshiddiqie, Wahiduddin Adams, dan Bintan R. Saragih atas kasus pelanggaran etik Anwar Usman yang saat itu menjabat Ketua MK.
Dari ketiganya, Jimly dan Wahiduddin perlu diberi catatan. Terlepas dari kapasitas keilmuwan dan pengalaman khususnya sebagai Ketua MK pertama, Jimly kini merupakan politisi dan anggota DPD yang menjadikan imparsialitas di MKMK patut dipertanyakan. Tanda tanya yang sama juga dialamatkan kepada Wahiduddin yang mengadili koleganya, bahkan ia sendiri juga merupakan Hakim Konstitusi Terlapor pada kasus dimana kesembilan Hakim Konstitusi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Dengan kata lain, Ridwan yang duduk di MKMK permanen juga mengantongi tanda tanya ini karena ia akan mengadili koleganya.
Celah Politik
Genealogi peradilan konstitusional adalah peradilan politik yang menjadikan MK selalu menjadi sasaran politisasi, termasuk MKMK. Bila ditelisik, kerancuan pembentukan MKMK juga diakibatkan oleh watak politik di luar MK.
Maka tersebutlah DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang yang memperlihatkan pola politik hukum lepas tanggung jawab untuk memperbarui UU MK secara proporsional. Ketika MK berdiri tahun 2003, pembentuk undang-undang mengkonstruksikan Pasal 86 UU MK dengan memberi ruang kepada MK untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kala itu, pembentuk undang-undang menilai belum adanya pengalaman dalam praktik peradilan konstitusional mengharuskan UU MK dirancang secara terbuka.
Pasal itulah yang kemudian menjadi rahim bagi Peraturan MK (PMK) yang justru lebih banyak berisi regulasi yang mengikat keluar (regelling), padahal regulasi kelembagaan seharusnya mengikat ke dalam (beschikking). Pola politik hukum ini bertahan hingga 20 tahun kemudian dan tumbuh bagai kanker dimana pembentuk undang-undang menilai MK lebih cakap untuk mengatur segala urusannya, termasuk membentuk MKMK. Alhasil, PMK justru menjadi kompensasi atas kerja pembentuk undang-undang yang tidak optimal dalam merumuskan UU MK.
Dari pola ini kemudian MK membuka ruang diadakannya MKMK Banding dalam PMK 1/2023, yang berjalan bila MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Hakim Terlapor. Hal itu, sadar atau tidak, merupakan celah lain masuknya tangan-tangan politik pada mekanisme penegakan etik. Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 atas kasus etik Anwar Usman merupakan contohnya. MKMK yang diketuai Jimly terjebak dalam muslihat Anwar dan kolega. Apabila Anwar di-PTDH, MKMK menilai, kasus etik itu akan berlarut-larut karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 PMK 1/2023, Anwar diberi hak membela diri melalui mekanisme banding. Sedangkan penyelenggaraan Pilpres kian dekat.
Argumentasi Jimly bisa diperdebatkan. Bila berkaca pada linimasa penyelesaian kasus etik yang dibatasi selama 30+15 hari, MKMK Banding sebenarnya masih bisa dibentuk dan bertugas sebelum Pilpres berlangsung. Sementara merujuk Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman, MKMK seharusnya memerintahkan diulangnya RPH perkara batas usia Capres/Cawapres karena Anwar terbukti melanggar prinsip integritas dan kehadirannya dalam RPH memengaruhi pendirian koleganya.
Bila dipahami benar, Putusan MKMK itu sangat jauh dari ideal karena jelas meneroka jalan aman di tengah arus politik maha kuat di perkara batas usia Capres/Cawapres. Persoalan yang barangkali melatarbelakangi putusan itu bisa jadi ihwal bagaimana mungkin memecat Anwar yang memiliki kekuatan politik besar di balik toga hakimnya.
Terlepas dari nuansa politik yang telah begitu jauh menjamah MK, dibentuknya MKMK permanen untuk saat ini masih dapat diapresiasi meski jauh dari ideal. Ke depannya, pola politik hukum pembaruan UU MK seharusnya lebih proporsional, di mana pembentuk undang-undang memberi desain konstitusional bagi MKMK yang tidak lagi melibatkan Hakim Konstitusi aktif. Pembentuk undang-undang bisa saja melibatkan MK dalam pengisian anggota MKMK, namun bukan sebagai pembentuk dan pemain tunggal.
Idealnya, MK dapat bertindak sebagai salah satu lembaga pengusul dengan mengusulkan mantan Hakim Konstitusi dengan rekam jejak positif untuk menduduki kursi MKMK. Pelibatan KY seharusnya dapat dipertimbangkan dalam pengusulan ini. Sebab berdasarkan Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 atas pengujian Pasal 27A ayat (2) huruf b, tidak dilibatkannya KY hanya dalam hal anggota MKMK, tidak dalam hal pengusulan anggota MKMK. Sementara satu kursi lainnya dapat diisi oleh akademisi berlatar belakang hukum sebagaimana yang telah dilakukan. Desain ini ditutup dengan pelantikan oleh Presiden, bukan lagi oleh Ketua MK.
Sumber : https://timesindonesia.co.id/kopi-times/482351/menyoal-majlis-kehormatan


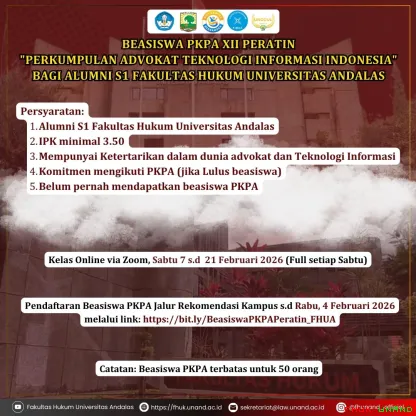

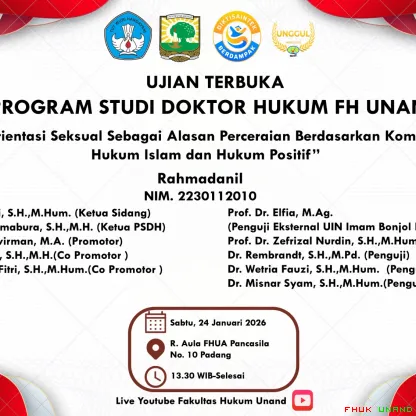
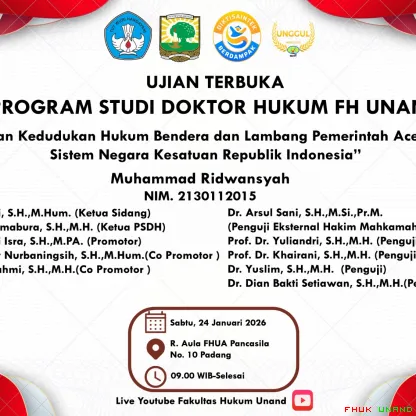
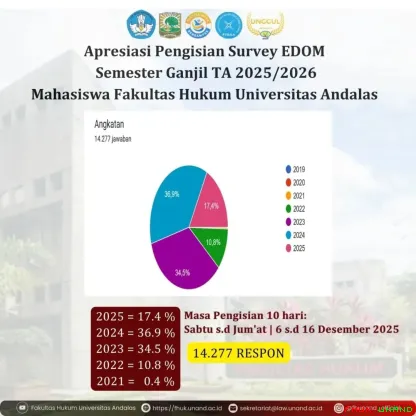

Komentar