MK Dan Krisis Konstitusionalitas
Ditulis Oleh : Ilhamdi Putra, SH., MH
Diterbitkan Oleh : Padang Ekspres, 15 Mei 2025
MK mengalami titik balik ketika Ketua MK, Akil Mochtar, menjadi tersangka kasus suap sengketa pilkada pada tahun 2013. Kasus Akil membuka kotak pandora bagi peradilan konstitusional itu, baik dalam hal pelanggaran etik beruntun sejumlah Hakim Konstitusi, hingga penurunan kualitas putusan di mana MK perlahan kehilangan sense of constitutionality.
Setelah Akil, ada pula Arief Hidayat yang secara beruntun melakukan pelanggaran etik, lalu Patrialis Akbar yang bertemu dengan pihak berkepentingan dalam perkara serta membocorkan draf putusan MK yang masih bersifat rahasia. Paling memalukan adalah Guntur Hamzah dan Anwar Usman. Guntur memalsukan putusan hanya 5 jam setelah dilantik sebagai Hakim Konstitusi, jabatan itupun ia peroleh melalui skandal politik, sementara Anwar dengan memanfaatkan jabatan sebagai Ketua MK menolong kemenakannya untuk berkontestasi dalam pilpres 2024. Arief, Guntur dan Anwar adalah tiga Hakim Konstitusi bermasalah yang masih menjabat dan menjadi bukti degradasi integritas Hakim Konstitusi.
Pergeseran Peran MK
Dekade pertama MK (2003-2013) merupakan tahun-tahun di mana peradilan konstitusional itu mengeluarkan putusan-putusan monumental bernuansa sense of constitutionality. Sebutlah Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang legendaris karena mencegah terjadinya privatisasi ketenagalistrikan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ada pula Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 yang memulihkan hak pilih warga negara sekalipun tidak terdaftar dalam DPT, atau Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 yang mewajibkan seluruh partai untuk melakukan verifikasi sebagai syarat kepesertaan pada pemilu legislatif 2014.
MK memang tidak sempurna di paruh pertama, setidaknya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menghapus kewenangan KY untuk mengawasi Hakim Konstitusi dapat dilihat sebagai sifat pragmatis Hakim Konstitusi yang menciptakan pembelahan antara hakim sebagai jabatan dan hakim sebagai kewenangan mengadili.
Meski begitu, setidaknya MK pada dekade pertama mampu tampil dengan putusan-putusan yang mengandung pertimbangan hukum berbobot sebagai bentuk kreasi aktif hakim dan tidak sekadar membeo makna undang-undang sebagaimana yang dimaksud pembentuknya.
Keadaan ini berubah pada dekade kedua (2014-2024). MK terjebak di tengah arus kuat pusaran politik. Maka lahirlah Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang membiarkan dilakukannya pengebirian terhadap KPK dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mencari pembenaran atas persoalan konstitusionalitas proses pembentukan UU Cipta Kerja. Puncaknya terjadi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengidap cacat hukum serius demi melanggengkan dinasti politik Joko Widodo dan Putusan MK Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang mengabaikan terjadinya kecurangan TSM dalam kemenangan Prabowo-Gibran pada pilpres 2024.
Di luar dua putusan terakhir, fenomena pergeseran peran MK sebagai aktor tunggal rekonsiliasi konstitusional didokumentasikan oleh Yance Arizona dalam risetnya, Politik Legislasi Presiden Joko Widodo dan Independensi Mahkamah Konstitusi (2024). Yance yang menganalisis 78 undang-undang dan 277 putusan MK berkaitan dengan politik, ekonomi, lembaga penegakan hukum dan kebebasan sipil memaparkan, bahwa MK kehilangan sense of constitutionality pada pengujian undang-undang yang dibentuk melalui proses legislasi yang banal di era pemerintahan Joko Widodo.
Temuan Yance menggambarkan peta posisi MK di Indonesia yang telah memasuki gerbong negara-negara dalam fase kemunduran demokrasi, seperti yang terjadi pada peradilan konstitusional di Hungaria, Turki, Venezuela dan Russia. Angela Di Gregorio dalam Contitutional Courts in The Context of Contitutional Regression: Some Comparative Remarks (2019) menganalisis, celah intervensi kepada MK di banyak negara jamaknya terjadi melalui manipulasi terhadap aturan main pengisian jabatan Hakim Konstitusi sehingga menghasilkan hakim-hakim loyalis pada kekuasaan yang memberinya jabatan.
Pengamatan senada diungkap Wicaksana Dramanda (2002), bahwa politisasi yudisial bertujuan untuk “menetralisasi” fungsi MK sebagai penyeimbang kekuasaan politik yang dilakukan melalui dimensi kelembagaan dan dimensi individual Hakim Konstitusi.
Kembalinya Sense of Constitutionality?
Seolah membasuh diri, MK tampak berusaha mengembalikan peran aslinya yang lama ditinggalkan dan menjemput jejak sense of constitutionality melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 222 UU Pemilu inkonstitusional karena melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Putusan ini menjadi angin segar di tengah gersangnya pertimbangan MK pada 33 putusan terdahulu yang menolak pembatalan pasal tersebut.
Terbaru adalah Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan 29 April 2025. Dalam putusan itu, MK menilai kritik merupakan bentuk pengawasan, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga hanya individu atau perseorangan yang dapat melaporkan terjadinya pencemaran nama baik di media elektronik.
Kini, MK dihadapkan pada anasir kebangkitan Orde Baru di balik perubahan UU TNI, dwi fungsi militer di tengah minimalisnya pengawasan DPR atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang berjalan menuju totalitarianisme. Sejak UU Nomor 3 Tahun 2025 disahkan pada 20 Maret 2025 dan ditandatangani Presiden beberapa hari setelahnya, Koalisi Masyarakat Sipil dan berbagai elemen masyarakat serta mahasiswa menyadari bahwa MK adalah harapan terakhir untuk menjegal bangkitnya Soehartoisme dari kubur.
Pertanyaan kuncinya: apakah MK benar-benar telah menjemput sense of constitutionality yang lama ditinggalkan dan mencegah terbentuknya pemerintahan militeristik, serta memaksa tentara pulang ke barak melalui pembatalan UU Nomor 3 Tahun 2025 seraya melarang militer menduduki jabatan sipil?
Setidaknya ada dua sisi untuk mengamati jawaban atas pertanyaan itu, yakni gambaran bagaimana kekuasaan di Indonesia berjalan hari ini dan bagaimana peran Hakim Konstitusi dalam menentukan arah demokrasi.
Steven Levitsky dan Lucan Way (2010) memperkenalkan varian rezim hibrida yang mengawinkan cara kerja pemerintahan otoritarian dengan demokrasi elektoral, di mana rezim yang mereka istilahkan sebagai otoritarianisme kompetitif itu memiliki ciri yang ada pada Indonesia hari ini. Bahwa institusi-institusi negara dan mekanisme demokrasi elektoral dimanfaatkan untuk mempertahankan legitimasi penguasa. Maka berkacalah pada Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024, serta Prabowo yang seolah terpasang tali kekang dari tangan Joko Widodo melalui Gibran dan sederet menteri bertuan ganda.
Lantas, bagaimana dengan MK?
Secara teoritis Hakim Konsitusi memang terikat pada praduga keabsahan, namun mereka tetaplah manusia yang memiliki kehendak bebas dan subjektivitas. Sedangkan pada arasnya, keberpihakan Hakim Konstitusi terhadap perkara adalah bentuk sikap tindakan bebas yang melepaskan diri dari paradigma praduga keabsahan. Secara bersamaan keberpihakan itu juga merupakan bentuk tindakan tidak bebas di mana Hakim Konstitusi mengikatkan diri pada kaidah-kaidah kognisi. Keadaan inilah yang disebut oleh antropolog hukum, Sally Falk Moore (1971), sebagai ketiadaan independensi. Sederhananya, kebebasan adalah bentuk lain dari keterikatan, bahkan keterpengaruhan. Moore menilai bahwa bagaimanapun hukum dibangun membentuk independensi, namun “independensi” tetap saja dilahirkan dari keterpengaruhan. Maka independensi tidak lain dari bentuk keberpihakan. Di sinilah naluri Sang Negarawan berbicara meski naluri itu berbentuk keberpihakan, dan ketika itu sense of constitutionality dapat ditemukan.



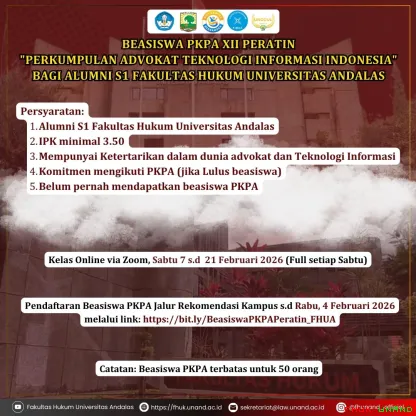

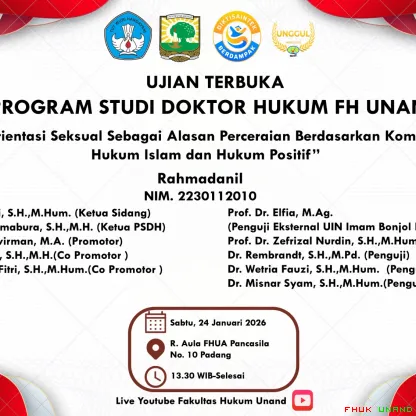
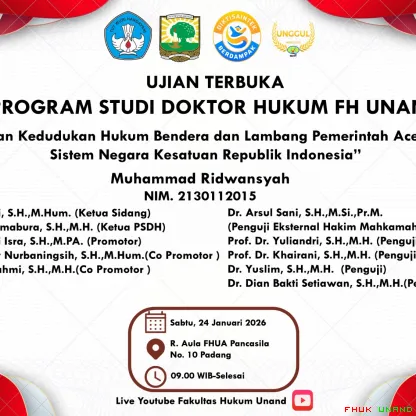
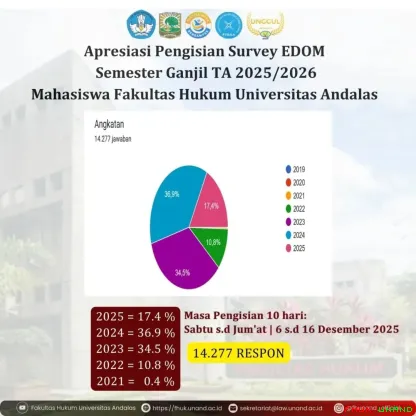

Komentar